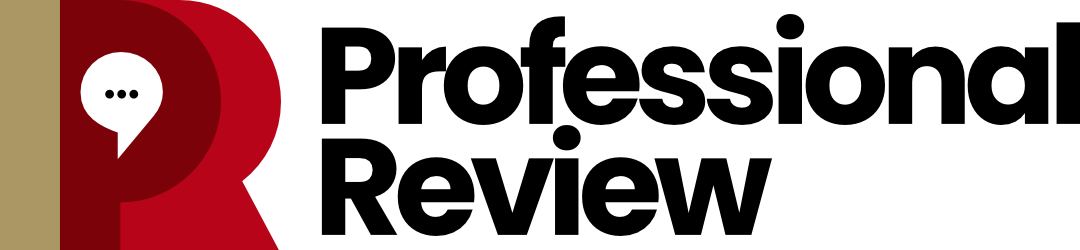Pada 3 Mei 2024, China berhasil meluncurkan Chang’e 6, sebuah misi ambisius yang bertujuan mengambil sampel batuan dari sisi terjauh bulan, wilayah yang tidak terlihat dari Bumi. Langkah ini merupakan bagian dari program luar angkasa China yang konsisten dan berkelanjutan, dengan tujuan ambisius mencapai target pada tahun 2030 untuk mendaratkan astronot serta membangun pangkalan di permukaan bulan.
Langkah China ini memunculkan pertanyaan penting: apakah program luar angkasa ini akan memperkuat tujuan damai luar angkasa bagi seluruh umat manusia sebagaimana yang tercantum dalam Traktat Luar Angkasa PBB 1967? Ataukah justru memperkeruh rivalitas penguasaan luar angkasa, mengingat China dan Rusia tidak bergabung dalam Artemis Accords yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sejak tahun 2020?
Astropolitik dalam Perspektif Modern
Everett C. Dolman dalam bukunya “Astropolitik” (2001) menjelaskan konsep ini sebagai visi realis dari kompetisi antarnegara terkait kebijakan antariksa. Negara-negara bukan hanya berkompetisi, tetapi juga berusaha mengembangkan dan mempengaruhi tata kelola internasional mengenai keterlibatan manusia di luar angkasa. Dolman membagi wilayah antariksa menjadi empat: Terra, Earth Space, Lunar Space, dan Solar Space. Kompetisi di wilayah Earth Space sudah terlihat jelas dengan banyaknya satelit komunikasi dan militer yang ditempatkan di ruang ini.
Astropolitik erat kaitannya dengan kajian geopolitik, bahkan saling melengkapi. Geopolitik membahas tentang interaksi antar kelompok manusia dalam konteks kekuasaan dan lokasi geografisnya. Sir Halford Mackinder dengan teori Heartland dan Alfred Thayer Mahan dengan konsep Sea Power memberikan teori yang kuat dan berpengaruh dalam strategi militer banyak negara. Kini, luar angkasa mulai dipandang sebagai heartland baru, di mana banyak negara berlomba-lomba mengembangkan teknologi untuk mendaratkan manusia di bulan dan tinggal di sana.
Rivalitas dan Kepentingan Ekonomi di Luar Angkasa
Rivalitas di luar angkasa tidak berakhir dengan berakhirnya Perang Dingin. Sebaliknya, dorongan untuk mencapai keuntungan ekonomi dan strategis semakin masif, terutama di bulan yang kaya dengan mineral seperti besi, titanium oksida, dan helium-3, yang penting untuk bahan bakar roket dan fisi nuklir. Bulan juga memiliki gravitasi yang hanya 1/6 dari gravitasi Bumi, yang memungkinkan peluncuran lebih efisien dan hemat energi dari permukaan bulan dibandingkan dengan dari Bumi.
Menurut teori Dolman, Lunar Space adalah tempat strategis untuk penguasaan luar angkasa. Penguasaan wilayah ini akan memudahkan tata kelola satelit di Earth Space dan menjadi pangkalan untuk eksplorasi lebih jauh ke Solar Space. Sehingga, koordinasi akan jauh lebih mudah jika permukaan bulan dikuasai dan berfungsi sebagai pit stop.
Artemis Accords dan Ketegangan Internasional
Namun, ketegangan muncul ketika Amerika Serikat, melalui Artemis Accords, gagal mengajak China dan Rusia bergabung. Fakta ini menunjukkan bahwa rivalitas tetap ada, tidak hanya di Bumi, tetapi juga di luar angkasa, dan kini telah memasuki dimensi militer. Kebijakan berbagai negara mencerminkan perbedaan persepsi dalam pengelolaan luar angkasa, seringkali mengarah pada dominasi atau bahkan hegemoni militer.
Rusia, misalnya, telah melakukan uji coba anti-satelit (ASAT) pada tahun 2021 dengan menghancurkan satelitnya sendiri, menghasilkan ribuan keping sampah antariksa yang berpotensi membahayakan satelit lain dan astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS). Saat ini, Rusia dipercaya sedang mengembangkan dan menempatkan senjata nuklir di luar angkasa.
Di sisi lain, Amerika Serikat membentuk United States Space Force (USSF) pada 2019 sebagai bagian dari restrukturisasi Angkatan Udara. USSF direncanakan menggelar latihan militer pertama di orbit Bumi pada 2025 dengan nama Victus Haze, melibatkan perusahaan seperti Rocket Lab National Security dan True Anomaly.
Kesadaran dan Potensi Antariksa di Indonesia
Indonesia juga tidak ketinggalan dalam perkembangan antariksa. Banyak lembaga di Indonesia yang khusus mengkaji pemanfaatan antariksa untuk kepentingan nasional. National Air and Space Power Center Indonesia (NASPCI) bekerja sama dengan Strategic ASEAN International Advocacy & Consultancy (SAIAC) dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) mengadakan lokakarya Diplomatic Workshop pada 25 April, membahas peran penting satelit dan antariksa.
Ketua NASPCI, Marsma TNI Dr. Penny Radjendra, S.T., M.Sc., M.Sc., menekankan pentingnya membangun kesadaran antariksa bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan teknologi dan pemanfaatan antariksa bersama.
Kesadaran antariksa ini penting untuk membangun kemampuan identifikasi kepentingan nasional Indonesia di antariksa. Hal ini dapat dimulai dengan keselarasan pencapaian Visi Indonesia Digital 2045 dan pengembangan ekonomi digital 2030.
Pendekatan ekonomi sangat penting untuk mengembangkan teknologi luar angkasa yang tidak murah dan mudah. Pelibatan sektor swasta sudah terbukti berhasil di AS dengan keterlibatan SpaceX dan Blue Origin oleh NASA. Tantangan bagi pemerintah baru Indonesia adalah menarik minat investor untuk melirik teknologi ruang angkasa dengan potensi ekonominya. Kehadiran Starlink di Indonesia memberikan ruang khusus untuk mengeksplorasi potensi dan keuntungan ekonomi dari teknologi luar angkasa.
Indonesia perlu segera membentuk kebijakan antariksa yang memuat visi jangka panjang untuk menghadapi ancaman militer dan non-militer di luar angkasa. Seperti China yang sedang mempercepat visinya dengan mewujudkan mitos Dewi Chang’e sebagai Dewi Bulan dalam program luar angkasanya. Perlu diingat, nenek moyang Indonesia adalah pelaut ulung yang navigasinya mengandalkan antariksa dalam mengarungi samudera hingga benua Afrika sejak abad ke-5 Masehi. Dengan warisan tersebut, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting dalam arena astropolitik global.